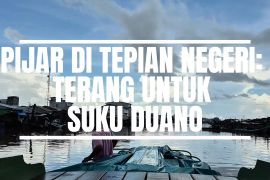Di tepi batas energi, agar Yusuf tetap bisa melaut

Pekanbaru (ANTARA) - Subuh belum sempurna datang ketika perahu-perahu kecil itu mulai meninggalkan dermaga kayu Concong Luar. Di atas gelombang yang memantulkan cahaya lampu petromaks, bayangan lelaki berusia lanjut tampak mengayun dayung dengan ritme yang lahir dari kebiasaan puluhan tahun. Ia adalah Yusuf, seorang nelayan dari Suku Duano — suku laut yang hidup di antara pasang surut, di batas laut dan darat, di antara keterpencilan dan keteguhan.
“Pergi jam dua belas malam, pulang jam empat subuh,” katanya lirih, matanya menatap arah muara, seolah menyimpan rahasia laut yang tak pernah habis diceritakan.
Di perahunya yang sempit, Yusuf membawa jala panjang 14 meter dan harapan yang tak kalah panjang. Ia tidak menuntut banyak: cukup energi untuk menggerakkan mesin tuanya, cukup angin bersahabat untuk menuntun ke perairan Busung, dan cukup hasil tangkapan untuk menghidupi tiga anaknya — dua di antaranya kini tengah menempuh kuliah.
“Kadang ada, kadang tak ada,” ucapnya, tersenyum getir. Tapi senyum itu bukan tentang putus asa, melainkan tentang kebiasaan: laut tidak selalu memberi, namun ia selalu menanti.
Concong Luar, sebuah desa di ujung timur Kabupaten Indragiri Hilir, adalah potret nyata keterpencilan Indonesia. Dari Pekanbaru, dibutuhkan delapan jam perjalanan darat menuju Tembilahan, lalu dua jam lagi menyeberang dengan kapal kayu menuju desa yang di sekitarnya hanya ada hutan bakau dan laut. Di sanalah Suku Duano menetap — suku yang oleh banyak orang disebut Orang Laut, atau Orang Concong.
Mereka dulu tinggal di perahu-perahu rumah, berpindah dari satu muara ke muara lain. Rumah mereka adalah laut, halaman mereka adalah ombak. Kini sebagian menetap di pesisir Concong, membangun rumah di atas kayu dan menambatkan hidup pada satu kata: melaut.
Setiap hari, mereka mencari udang rebon — bahan utama ebi yang menjadi ikon Indragiri Hilir. Udang kecil itu direbus sebentar, lalu dijemur selama dua hingga tiga hari hingga kering sempurna dan berwarna oranye pucat. Tak ada bahan pengawet, hanya panas matahari dan udara asin yang jadi sahabat setia. Dari hasil kecil itulah mereka hidup, menghidupi keluarga, dan menjaga tradisi.
Namun di balik kesederhanaan itu, ada satu hal yang menjadi nadi kehidupan mereka: energi.
Di Concong, solar bukan sekadar bahan bakar — ia adalah darah yang mengalirkan kehidupan. Tanpa solar, perahu tak bisa berangkat. Tanpa solar, jaring tak bisa ditebar. Dan tanpa solar, tidak ada ebi yang bisa dijemur di halaman rumah-rumah kayu itu.
Afrain, nelayan Duano lain yang tinggal di Desa Panglima Raja, tahu benar rasanya hidup di masa ketika solar sulit didapat. “Dulu kami beli di warung eceran, harganya sampai sepuluh ribu per liter,” kenangnya. “Hasil melaut tak cukup untuk makan.”
Kini, dengan hadirnya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Solar Satu Harga, hidup perlahan berubah. Ia bisa membeli solar resmi seharga Rp6.800 per liter — harga yang sama dengan nelayan di kota besar. “Dapat 22 liter, cukup buat seminggu melaut,” ujarnya sambil menenteng jerigen yang masih meneteskan sisa solar.
Bagi Afrain, BBM bersubsidi bukan sekadar kebijakan, melainkan bentuk keadilan yang nyata. “Dulu hasil melaut hanya cukup untuk hidup hari ini. Sekarang bisa simpan sedikit untuk anak sekolah,” katanya, matanya menatap laut yang ia sebut “madrasah kehidupan.”
SPBN 18292068 di Concong Luar berdiri tidak hanya sebagai tempat pengisian bahan bakar, tetapi juga simbol keberlanjutan hidup masyarakat pesisir. Di sinilah denyut ekonomi laut berawal setiap pagi.
Hendi, pengawas SPBN, membuka catatan di tangannya. “Permintaan solar rata-rata sepuluh ribu liter per hari,” katanya. “Stok kami cukup untuk satu minggu, lima puluh ribu liter.”
Ia dan dua operator menjaga pompa dari pagi hingga sore, menyesuaikan jadwal para nelayan. Kadang kala, anjing-anjing penjaga menggonggong di antara tongkang-tongkang kayu — satu-satunya sistem keamanan di tempat yang jauh dari aparat.
“Kalau hujan, nelayan tak datang ambil solar,” ujar Hendi sambil tersenyum. “Besoknya pasti ramai.”
SPBN itu kini melayani sekitar 200 nelayan resmi yang terdaftar berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Tak semua bisa mengambil. Ada rekomendasi dari dinas, ada batas kuota. Tapi bagi Yusuf dan Afrain, keteraturan itu membawa rasa aman. Mereka tahu, solar akan selalu ada saat dibutuhkan.
Di balik lancarnya solar yang mengalir ke Concong, ada rantai panjang distribusi energi yang bergerak diam-diam, menembus muara, melewati gelombang, dan berlabuh di dermaga kecil.
Dari Fuel Terminal (FT) Tembilahan, bahan bakar dikirim menggunakan kapal-kapal distribusi milik PT Elnusa Petrofin — Muara Raya, Persahabatan, Anugerah Indah — membawa puluhan ribu liter solar setiap pekan.
Fahrudin, manajer FT Tembilahan, menjelaskan, “Kami menjaga pasokan untuk wilayah 3T, termasuk Concong dan sekitarnya. Tembilahan adalah jantung distribusi energi di Indragiri Hilir.”
Terminal ini memiliki kapasitas tangki hingga 15.000 kiloliter, lengkap dengan sistem keamanan otomatis, pengukur stok digital, dan dermaga berkapasitas 3.500 DWT. Setiap hari, 800 hingga 850 kiloliter bahan bakar bergerak keluar dari depot ini — sebagian besar menuju pesisir terpencil seperti Concong.
“Kami memastikan energi hadir di setiap titik kehidupan, bahkan di ujung negeri,” tegas Fahrudin. “Karena keadilan energi bukan sekadar slogan, tapi napas yang harus terus dijaga.”
Sore menjelang malam di Concong adalah lukisan yang menenangkan. Anak-anak berlarian di jembatan kayu, perempuan menjemur udang terakhir hari itu, dan dari kejauhan, lampu-lampu kapal nelayan mulai menyala di atas permukaan laut.
Dulu, sebelum ada SPBN dan solar satu harga, malam di kampung ini gelap. Hanya cahaya lentera dari minyak tanah yang temaram. Kini, generator rumah menyala, kulkas kecil berdesing pelan, televisi memutar berita dari kota.
Energi telah menyalakan cahaya — bukan hanya di rumah-rumah, tapi juga di hati mereka.
Kehadiran energi membuat kehidupan Suku Duano perlahan bertransformasi. Industri kecil tumbuh: pembuatan ikan asin, pengeringan ebi, bahkan perdagangan udang bayi lobster. Semua memerlukan bahan bakar, semua digerakkan oleh solar yang datang tepat waktu.
Namun di balik geliat ekonomi itu, ada filosofi tua yang tetap dijaga: hidup berdampingan dengan laut.
Suku Duano tahu bahwa laut bukan milik mereka; mereka hanya bagian dari laut. Alam memberi, mereka menjaga. Itulah sebabnya setiap kali badai datang, mereka tak pernah menyalahkan siapa pun. Hanya berdoa agar esok angin bersahabat.
Yusuf kembali ke rumahnya menjelang fajar, membawa 50 kilogram udang campur di ember plastik. Di matanya, ada lelah, tapi juga kebanggaan. Ia tahu, hasil itu cukup untuk hari ini, mungkin juga besok.
“Solar itu seperti darah,” katanya pelan, “kalau berhenti, kami juga berhenti.” Dalam mengalirkan denyut pembakaran tersebut, kadang nelayan seperti "Yusuf-Yusuf" yang lain, tidak begitu paham maupun tersirat dari mana energi itu berasal. Baginya energi berkeadilan bagi rakyat yang ia pahami entah dari mana berasal, sudah lebih dari cukup.
Langit energi negeri ini tak pernah benar-benar tenang. Di antara gelombang minyak mentah dan angin neraca perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berdiri sebagai nahkoda menyusun arah agar kapal besar bernama Indonesia tak oleng diterpa arus impor, agar Yusuf tetap melaut.
Bersama para pelaku usaha minyak dan gas, baik raksasa Pertamina maupun para pemain swasta yang menyalakan lampu di setiap SPBU negeri ini, mereka sepakat pada satu hal: menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan. Antara isi tangki rakyat dan isi dompet negara.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut langkah ini sebagai “jalan tengah”, bukan sekadar kebijakan, tapi ikhtiar agar api di dapur-dapur rumah tangga tetap menyala, sementara neraca perdagangan tak terbakar defisit. Dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024, pasal demi pasal menjadi kompas: setiap keputusan tentang bahan bakar, tentang komoditas yang menggerakkan roda bangsa, mesti ditimbang oleh para pembina sektor dengan kepala dingin dan hati jernih.
Negeri ini tak pernah menutup pintu bagi impor. Justru di sanalah denyut pasar terasa. Lihatlah bagaimana pangsa BBM non-subsidi di SPBU swasta tumbuh: sebelas persen naik pada 2024, lalu menyentuh lima belas persen hingga Juli 2025. Angka-angka itu bukan sekadar statistik, melainkan kisah tentang geliat ekonomi, tentang deru kendaraan di jalan-jalan yang tak pernah sepi.
Namun, di balik keterbukaan itu, pemerintah menyiapkan kendali. Impor boleh, tapi terukur. Karena setiap tetes minyak yang datang dari luar negeri adalah bagian dari keseimbangan yang rapuh—antara kebutuhan hari ini dan ketahanan esok.
Kebijakan ini, kata pemerintah, bukan batu yang kaku. Ia lentur seperti air, bisa berubah arah bila pasokan dalam negeri melimpah atau bila kas negara perlu bernapas. Dan di tengah semua hitung-hitungan itu, Pertamina Patra Niaga masih menyimpan cadangan: kuota impor 34 persen, sekitar 7,52 juta kiloliter—cukup untuk menyalakan ribuan SPBU hingga Desember 2025, termasuk tambahan jatah bagi para pengusaha swasta.
Di balik angka dan aturan, terselip harapan: agar bangsa ini tak hanya mandiri dalam produksi, tapi juga bijak dalam menjaga nyala energi. Karena pada akhirnya, bahan bakar bukan sekadar cairan dalam tangki—melainkan darah yang mengalir di nadi ekonomi Indonesia.
Kebijakan itulah yang membuat terpencil tak lagi terisolir. Di tepi laut yang sunyi itu, Suku Duano hidup dalam keheningan yang tak berarti keterasingan. Mereka terpencil, ya. Tapi tidak lagi terkucil. Karena di sana, di ujung laut Sumatra, nadi energi terus menyala — menyalakan perahu, menyalakan kehidupan, menyalakan harapan.
Pewarta : Afut Syafril Nursyirwan
Editor:
Afut Syafril Nursyirwan
COPYRIGHT © ANTARA 2026